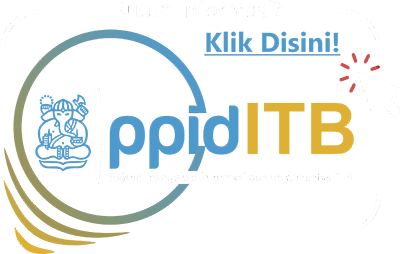Seorang pebisnis mesti memahami perbedaan budaya dapat membentuk gaya interaksi di berbagai konteks bisnis. Negara-negara seperti Indonesia, Tiongkok, dan Arab Saudi cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan hierarkis yang bersifat top-down, di mana keputusan dipusatkan pada segelintir orang.
Sebaliknya, negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark lebih memilih pendekatan egaliter, dengan kepemimpinan yang lebih merata dan keputusan yang dibuat secara kolaboratif. Amerika Serikat dan Inggris juga cenderung ke arah kepemimpinan top-down, tetapi dengan struktur otoritas yang lebih egaliter dibandingkan negara-negara seperti Rusia dan India.
Demikian disampaikan Dr. N. Nurlaela (Lala) Arief, MBA, Pengajar pada SBM ITB, saat mengisi kursus terbuka daring dengan topik “Komunikasi Bisnis: Konteks Antarbudaya” pada Kamis (19/9). Dalam kursus yang digelar oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB tersebut, Lala membahas bagaimana perbedaan budaya memengaruhi komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pemberian umpan balik di dunia bisnis global.
Menurut Lala, ada risiko stereotip yang muncul akibat generalisasi budaya yang terbatas. Dia memperingatkan, bahkan manajer berpengalaman dapat terjebak dalam kesalahan ini ketika memimpin orang-orang lintas budaya. Salah satu poin penting adalah kompleksitas dalam mengelola tim internasional, di mana harapan terhadap kepemimpinan bisa sangat bervariasi tergantung pada norma budaya setempat.
Dalam kursus tersebut, Lala juga membahas perbedaan antara komunikasi berkonteks rendah dan berkonteks tinggi. Dalam budaya berkonteks rendah seperti Amerika Serikat dan Jerman, komunikasi cenderung lebih langsung dan eksplisit. Sebaliknya, budaya berkonteks tinggi seperti Jepang dan Prancis lebih mengandalkan komunikasi yang lebih halus dan bertingkat, di mana banyak hal disampaikan secara implisit melalui konteks. Lala menekankan bahwa kesalahpahaman sering kali terjadi ketika individu dari gaya komunikasi yang berbeda berinteraksi tanpa menyadari perbedaan tersebut.
Selain itu, setiap negara punya berbagai budaya dalam memberikan kritik. Prancis dan Australia dikenal memberikan umpan balik yang lebih langsung. Sementara Jepang cenderung memilih pendekatan yang lebih diplomatis dan tidak langsung. Kesadaran budaya sangat penting saat memberikan umpan balik dalam tim internasional, karena pendekatan yang berbeda bisa menyebabkan salah paham atau ketegangan.
Selain komunikasi dan umpan balik, kursus ini juga mengeksplorasi perbedaan budaya dalam persuasi, membangun kepercayaan, dan penyelesaian konflik. Budaya Barat seperti Amerika Serikat dan Jerman umumnya menggunakan pendekatan persuasi yang berbasis prinsip, di mana argumen dibagi menjadi komponen-komponen terpisah. Sementara itu, budaya Asia seperti Jepang lebih memilih pendekatan holistik yang melihat keseluruhan gambaran terlebih dahulu.
Demikian pula, cara membangun kepercayaan sangat bervariasi, dengan budaya berbasis tugas seperti Amerika Serikat dan Jerman yang menekankan kompetensi dan keandalan, sementara budaya berbasis hubungan seperti India dan Tiongkok lebih menekankan koneksi pribadi.
Menurut Lala, setiap budaya juga berbeda dalam menangani perbedaan pendapat. Negara seperti Belanda dan Jerman cenderung menerima perdebatan terbuka sebagai cara untuk mencapai solusi yang lebih baik. Sebaliknya, budaya seperti Indonesia dan Thailand cenderung menghindari konfrontasi demi menjaga harmoni dalam kelompok.
Penanggungjawab Program Kursus Terbuka ITB, Allya Paramita Koesoema, S.T., M.T., Ph.D., mengatakan kursus terbuka merupakan kelas yang dapat diakses tidak hanya oleh mahasiswa internal suatu perguruan tinggi, namun juga oleh kalangan luar, baik mahasiswa perguruan tinggi lain, maupun peserta dari professional industry dan umum.
“Di perguruan tinggi terkemuka di dunia seperti MIT, Stanford, dan lainnya, open course telah menjadi suatu kewajaran dan digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk showcase dari inovasi dan pembelajaran yang dimiliki, alat promosi atau gateway untuk mahasiswa baru, serta peningkatan reputasi dan branding dari perguruan tinggi,” jelas Allya.
Allya berharap kursus terbuka ini dapat berfungsi positif dalam pengembangan branding ITB, mendukung proses pembelajaran yang berkelanjutan, dan mendorong pembelajaran professional di ITB.
“Selain itu, program ini juga diharapkan dapat turut mendukung peningkatan IKU 5 dan QS ranking, khususnya dalam aspek academic reputation bagi ITB,” tambahnya.
Sebab, salah satu karakteristik pendidikan yang dapat mendukung perguruan tinggi menjadi World Class University adalah borderless learning, atau pembelajaran di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja.
“Program ini melibatkan semua fakultas yang ada di SBM. Kami sebagai perwakilan dari SBM, menyiapkan materi terkait dengan tema yang relevan dengan pengajaran mata kuliah Intercultural Communication dan Leadership Communication,” jelas Lala.